ARTICLE AD BOX
Pengetahuan adalah harta yang tak bisa dicuri pencuri, tak bisa diambil raja, tak bisa dibagi antarsaudara, dan tak menjadi beban. Semakin digunakan, semakin bertambah—itulah harta tertinggi.
FENOMENA banyaknya anak SMP dan SMA yang belum bisa membaca dengan lancar (atau bahkan belum bisa membaca sama sekali) merupakan indikator krisis literasi yang serius. Ini bukan hanya soal kemampuan teknis membaca, tapi cerminan dari masalah struktural, sosial, dan kultural dalam sistem pendidikan dan masyarakat. Jika siswa sudah duduk di SMP atau SMA tapi belum bisa membaca, berarti mereka ‘terangkat naik’ tanpa bekal kemampuan dasar. Ini menunjukkan ada ‘learning loss’ yang sangat parah.
Di banyak sekolah, ada tekanan untuk menaikkan kelas siswa meskipun belum memenuhi standar kompetensi. Ini dikenal sebagai fenomena social promotion — siswa dipromosikan ke jenjang berikutnya tanpa memperhatikan kesiapan akademiknya. Di samping itu, sebagian guru di daerah tertinggal atau di sekolah-sekolah tertentu menghadapi minimnya pelatihan pedagogis dan beban administratif tinggi, sehingga proses pembelajaran tidak maksimal. Belum lagi tantangan rasio guru-murid yang tinggi dan keterbatasan bahan ajar yang sesuai.
Dalam konteks sosial ekonomi, anak dari keluarga miskin, anak-anak buruh migran, atau yang tinggal di daerah terpencil, sering tidak mendapatkan stimulasi literasi di rumah. Membaca bukan kebiasaan harian, dan orangtua juga mungkin tidak bisa membantu. Akibatnya, mereka masuk sekolah tanpa kesiapan literasi awal. Dalam budaya pendidikan di banyak daerah, nilai lebih penting daripada makna. Guru dan orangtua lebih menghargai hafalan dan ujian daripada kemampuan memahami isi bacaan. Anak bisa naik kelas karena nilai dibuat ‘cukup’, walau tak bisa membaca dengan lancar.
Di banyak komunitas, budaya visual (video, TikTok, YouTube) menggantikan teks sebagai media utama interaksi dan hiburan. Anak-anak jauh lebih terbiasa menonton daripada membaca. Dapat dikatakan bahwa krisis literasi di tingkat SMP/SMA tidak hanya karena anak ‘tidak bisa’, tapi karena mereka tidak tumbuh dalam ekosistem budaya yang menghargai, memfasilitasi, dan menumbuhkan kebiasaan membaca. Ini adalah krisis budaya, bukan sekadar masalah kognitif.
Sloka di atas menyampaikan nilai luhur dari pengetahuan (vidyā) sebagai harta paling berharga dalam hidup manusia. Dalam konteks krisis literasi—di mana banyak anak SMP dan SMA belum bisa membaca—sloka ini menjadi cermin ironi sosial dan kultural yang menyakitkan: kita hidup di zaman yang penuh akses terhadap ‘kekayaan tertinggi’ (pengetahuan), tetapi banyak anak justru terputus dari warisan itu.
Sloka ini menekankan bahwa pengetahuan itu tidak bisa dirampas, tapi dalam kenyataan, anak-anak miskin, terpencil, atau termarjinalkan seolah ‘dirampas’ aksesnya terhadap pengetahuan karena tidak bisa membaca. Ini bukan karena kekurangan kemauan, melainkan karena sistem sosial dan budaya tidak menopang pembelajaran mereka.
Sloka menyatakan bahwa pengetahuan bertambah ketika dibagikan. Tapi dalam budaya kita, membaca dan belajar sering tidak dianggap penting atau mendesak, apalagi untuk anak-anak yang hidup dalam tekanan ekonomi dan sosial. Akibatnya, potensi pertumbuhan ini mandek. Kita menyia-nyiakan kekayaan yang justru ‘berlipat ganda’ saat digunakan.
Anak-anak yang tidak bisa membaca bukan sekadar tidak bisa ‘mengeja’, tapi terputus dari kemampuan untuk mengakses dunia pengetahuan. Sloka ini menggambarkan vidyā sebagai ‘sarva dhana pradhānam’ kekayaan dari segala kekayaan. Maka krisis literasi adalah kehilangan modal dasar manusia untuk tumbuh secara spiritual, sosial, dan intelektual.
Sloka ini secara tidak langsung mengingatkan bahwa pengetahuan itu bukan milik pribadi, tetapi harus diwariskan dan dibagikan. Maka, ketika ada generasi muda yang terjebak dalam kebutaan huruf, itu mencerminkan gagalnya masyarakat untuk menunaikan tanggung jawab kulturalnya dalam menyebarkan pengetahuan.
Sloka ini bisa dijadikan landasan moral dan filosofis dalam menggugah kesadaran masyarakat akan pentingnya mengatasi krisis literasi. Ia mengingatkan kita bahwa membiarkan anak-anak tumbuh tanpa kemampuan membaca adalah bentuk kemiskinan paling dalam—karena kita membiarkan mereka kehilangan kekayaan yang tak ternilai. 7

 3 hours ago
1
3 hours ago
1






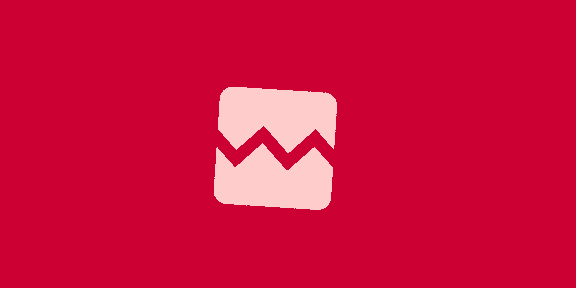
 English (US)
English (US)