ARTICLE AD BOX
Wahai Partha (Arjuna), kecerdasan yang salah, yang melihat dharma sebagai adharma, dan adharma sebagai dharma, serta tidak memahami apa yang seharusnya dan tidak seharusnya dilakukan, itu disebut kecerdasan dalam mode rajas (rajasik buddhi).
SAAT ini, orang dengan cara berpikir (logika) terbalik sangat lumrah. Orang rela ngutang demi beli gadget terbaru, liburan ke luar negeri, atau nongkrong di kafe mahal, padahal keuangannya lagi defisit. Status sosial dianggap lebih penting daripada keamanan finansial. Anak-anak muda rela nyicil iPhone terbaru atau motor gede demi status sosial, lebih penting terlihat sukses daripada benar-benar mapan. Beberapa orang membuat konten ekstrem dengan merendahkan diri sendiri, mempermalukan orang lain, atau menyebarkan berita palsu demi viralitas, hanya untuk mengejar likes, views, dan ketenaran instan, tanpa peduli pada harga diri, etika, atau dampak jangka panjang. Asal terkenal, berarti berhasil.
Di banyak kalangan, ada pembenaran bahwa mengambil jalan pintas (korupsi, nepotisme, kolusi) sah-sah saja selama itu untuk menghidupi keluarga atau ‘membalas budi’ kepada orangtua. Banyak siswa (dan kadang orangtua) lebih mengutamakan acara seremoni (wisuda megah, foto-foto mewah) daripada kualitas belajar, karakter, atau kemandirian finansial. Logika terbaliknya: pendidikan itu tentang pestanya, bukan proses belajarnya. Banyak orang memuja budaya hustle (kerja terus-menerus tanpa istirahat), mengabaikan kesehatan mental dan fisik, seolah-olah burnout adalah tanda sukses. Demikian seterusnya banyak contoh lain yang mengindikasikan logika terbalik.
Di era milenial, logika terbalik ini sering muncul akibat kombinasi kebutuhan validasi sosial, budaya instan, hilangnya prioritas nilai, dan kurangnya kontemplasi tentang kehidupan yang lebih dalam. Banyak keputusan dibuat berdasarkan ‘apa yang tampak keren’ dibandingkan ‘apa yang benar dan bijak’. Bahkan, Krishna pada teks di atas menyebutnya ‘buddhi yang rajasik’, di mana orang tidak bisa lagi membedakan apa yang benar dan salah, atau apa yang seharusnya didahulukan. Apa akar penyebabnya? Tentu karena ‘kekeruhan batin manusia, akibat dari gabungan kondisi psikologis, kognitif, spiritual, dan sosial’.
Dalam Advaita Vedanta, akar dari semua kekeliruan adalah Avidya, ketidaktahuan terhadap hakikat sejati diri dan realitas. Orang tidak melihat dunia sebagaimana adanya. Yang terlihat adalah bayang-bayang keinginan, ketakutan, dan konstruksi sosial. “Seperti orang melihat tali, tapi dikira itu ular.” Menganggap dunia luar sebagai sumber kebahagiaan sejati, lalu mengejar bayangan semu tanpa sadar bahwa itu semua tidak benar-benar memuaskan.
Yoga Sutra Patanjali menyebut Asmita, keterikatan pada identitas palsu: “Aku harus seperti ini supaya diakui”, “Aku tidak boleh kalah dari orang lain.” Ego membutakan pertimbangan rasional. Logika dikendalikan untuk membenarkan apa yang sudah diinginkan ego, bukan untuk mencari kebenaran objektif. Di sini, logika terbaliknya adalah membenarkan keputusan yang salah agar harga diri tetap terjaga. Zaman modern memperparah false consciousness. Budaya konsumerisme, media sosial, dan tekanan sosial membentuk nilai palsu: “Yang viral itu benar”; “Kalau tidak pamer, berarti gagal.” Lingkungan menciptakan distorsi nilai, sehingga orang bahkan tidak sadar dirinya sudah hidup dalam dunia ilusi.
Untuk mengatasi false consciousness itu, tradisi Hindu menawarkan beberapa solusi klasik yang saling melengkapi. Pertama, Viveka, artinya kemampuan membedakan antara: yang nyata dan tidak nyata, yang kekal dan tidak kekal, yang benar-benar bernilai dan yang hanya ilusi. Bagaimana membangun Viveka? Dengan latihan refleksi diri (ātma-vicāra), belajar dari guru yang mumpuni, belajar dari kitab suci (śāstra) otentik, seperti Upanishad, Gita, Sutra Yoga. Kedua, Vairagya (ketidakmelekatan), kemampuan untuk tidak terjebak atau melekat pada hal-hal yang berubah: harta, status sosial, pujian, kesenangan indria. Bagaimana mengembangkan Vairagya? Menyadari sifat dunia yang fana (anitya) dan penuh ketidakpuasan (duhkha), melatih diri untuk menikmati sesuatu tanpa bergantung padanya.
Ketiga, dalam banyak tradisi, diajarkan Satsangātve nissangātvam, dari berkumpul dengan orang bijak, muncullah ketidakmelekatan, kebijaksanaan, dan pembebasan. Caranya? Mendekat kepada komunitas spiritual yang fokus pada pencarian kebenaran, menjauhkan diri dari lingkungan yang penuh nafsu, pamer, dan tipuan sosial. 7

 2 hours ago
1
2 hours ago
1






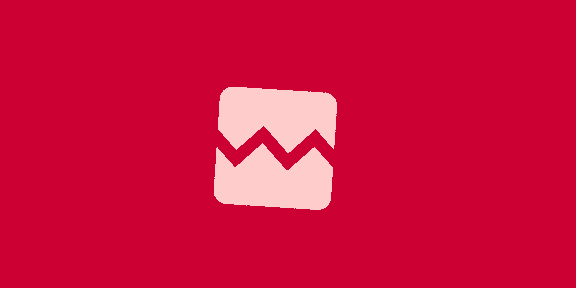
 English (US)
English (US)